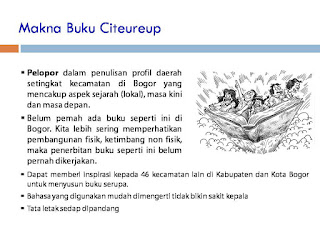Friday, August 7, 2015
Bedah Buku: Citeureup Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan
Peringati HUT, Indocement Gelar Bedah Buku
http://koranbogor.com/peringati-hut-indocement-gelar-bedah-buku/
KORANBOGOR.com, BOGOR
– Kepedulian PT. Indocement Tunggal Prakasa (ITP) Citeureup Kabupaten
Bogor melalui dana Corporate Sosial Responsibility Departemen yang digulirkan
melalui 5 Pilarpengembangan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, social
budaya agama & olahraga serta keamanan patut mendapat acungan jempol.
Menurut Direktur Eksekutif
Indocment Kuky Permana, saat ini CSR Indocement sudah berada tahap creating
shared value untuk msayarakat di wilayah binaan dan diharapkan dapat terbentuk
generasi yang lebih berkualitas dalam mencapai masyarakat mandiri yang
berkelanjutan. Hal itu dikatakan Kuky dalam bedah buku Citeureup yang ditulis
Anto Dwiastoro di Gedung Serbaguna Indocement, Kamis (6/7).
Acara bedah buku ini
menghadirkan sejarawan nasional, Edi Sudrajat, Direktur Research Center for
Institutiona Develpopment Unversitas Indonesia , Triarko Nurlambang, MA, Ph.D,
dan penulis buku Citeureup Anto Dwiastoro,dengan moderator wartawan senior
Kompas, Anton Wisnu Nugroho.
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan
HUT Indocement yang ke 40 tahun. “Dengan bedah buku ini diharapkan masayarakat
memahami kondisi Citeureup bahwa pengembangan masyarakat di wilayah Indocement
sudah tidak lagi berada dalam kondisi philantrophy (kedermawanan) tapi sudah menjajaki
suatu tahapan menuju masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan,”tegasnya.
Sementara itu Corporate
Secretary, Pigo Pramusakti yang membuka acara tersebut mengatakan bahwa
Indocment yang didirikan 40 tahun lalu, sudah mengalami 3 dekade, 10 tahun pertama
sudah mengubah kebijakan dari impor menjadi ekspor, decade kedua nasionalisasi
berupa penyerahan operasional ke para putra bangsa, dekede ke tiga menjadi
perusahan multinasional dan memberi kontribusi kepada masyakat (people) dan
planet melalui dana CSR.
Kegiatan bedah buku tersebut
dihadiri Camat Citeureup, Ketua MUI Citeureup, Ketua KNPI Citeureup serta
pemerhati budaya lokal hingga nasional. Yang menarik acara ini diisi oleh Orkes
Keroncong Tugu yang merupakan generasi Mayor Yance, sosok yang erat kaitannya
dengan isi buku tersebut. Buku ekslusif yang dikarang Anto Dwiastoro dan
dibiayai sepenuhnya oleh CSR Indocement ini bekerjasama dengan Yayasan Tapak
Citeureup, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Sebelumnya dilakukan
peluncuran Buku Citeureup pada Selasa (4/8) di Rumah Pintar Desa Tajur
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. (dang HP).
Tuesday, July 7, 2015
KH R Abdullah bin Nuh: Sang Ulama Pejuang
KH. RADEN
Abdullah bin Nuh:
Sang Ulama, Penyair dan
Pejuang Kemerdekaan RI
“Jika tidak ada kamus Indonesia-Arab-Inggris yang disusun Kiai Abdullah
bin Nuh dan Oemar Bakry, rasanya saya tidak akan bisa berbahasa Arab,” ujar
Prof. Dr. Machasin, MA pada tahun 2004. “Waktu saya kuliah, belum ada kamus
Indonesia-Arab, yang ada kamus Arab-Melayu Mahmud Yunus. Tapi bahasa Melayu kan
membingungkan,” sambung Prof. Machasin, yang juga pernah menjabat Direktur
Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Direktur Pendidikan
Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
Demikianlah arti penting kamus yang disusun Abdullah bin Nuh & Oemar
Bakry. Kamus ini pertama kali
diterbitkan 1959, tebalnya 330 halaman dan dihiasi gambar ilustrasi 28 halaman.
Pada 1990-an, kamus ini masih dicetak ulang.
Siapapun yang menyusun kamus, pastilah ia orang yang tekun dan
terpelajar serta mencintai ilmu. Soalnya menyusun kamus tiga bahasa bukan
pekerjaan gampang, diperlukan ketekunan, ketelitian, dan ilmu yang luas;
lagipula pada dasawarsa 1950-an, honornya tidak seberapa besar.
Sejak kecil, Abdullah bin Nuh memang dikenal sebagai pecinta ilmu, tekun
dan jenius. Dalam usia 13 tahun, ia mampu menggubah syair berbahasa Arab.
Rupanya bahasa Arab bukan hal asing bagi dirinya. Di usia balita, ia dibawa
keluarganya bermukim di Makkah selama dua tahun. Ia tinggal bersama Nyi Raden
Kalifah Respati, nenek dari ayahnya yang kaya raya dari Cianjur dan ingin
meninggal di Makkah. Pengalamannya tinggal di sana cukup meninggalkan kesan
khusus. Ia seringkali bercerita pada keluarganya tentang pedagang-pedagang
makanan pagi di Makkah yang menjajakan barang dagangan sambil berseru El
Batato ya Nas. “Kalau di Indonesia, tak ubahnya seperti
pedagang-pedagang yang ada di Yogya yang menjajakan dagangannya sambil berseru “Gudege
nggih den…. Gudege nggih den,” tuturnya kepada keluarga.
Abdullah bin Nuh menimba ilmu pertama kali di pesantren keluarganya, I‘anatut Talibil
Muslimin di Cianjur, dilanjutkan ke Madrasah Syamailul Huda, Pekalongan, Jawa
Tengah; lalu mengikuti gurunya ke Surabaya, Jawa Timur, untuk mendirikan
Hadramaut School (1922-1926). Tidak tangung-tanggung, ia belajar lebih jauh
lagi ke Jamiatul Azhar, Kairo, Mesir (1926-1928).
Sepulangnya dari Kairo, ia tingal di Ciwaringin, Bogor untuk mengajar Madrasah Islamiyah, lalu pulang ke Cianjur untuk
mengajar di pesantren keluarganya (1930). Tak lama kemudian ia dinikahkan
dengan R. Mariyah binti R. Haji Abdullah. Saat itu ia pulang-pergi Cianjur-Bogor untuk mengajar di madrasah dan sekolah menengah umum MULO (Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs). Tentu bukan perkara mudah dapat mengajar di
sekolah dengan sistem pendidikan Belanda seperti MULO.
Di masa itu, ia aktif
menyebarkan semangat nasionalisme anti penjajahan melalui ceramah dan pengajaran
di majelis taklim, pesantren dan di sekolah-sekolah. Ia bersahabat dengan para ulama di Bogor, Cianjur dan Sukabumi, antara lain dengan KH Ahmad Sanusi dari Cantayan,
Sukabumi, yang sangat terkenal waktu itu. KH Ahmad Sanusi sempat dibuang ke
Tanah Tinggi, Batavia Centrum selama enam tahun (1928-1934).
Sama halnya dengan Abdullah bin Nuh, KH Sanusi juga seorang yang tekun,
jenius, dan pejuang kemerdekaan. KH Ahmad Sanusi menulis 480 (empat ratus
delapan puluh!) karya tulis dalam bahasa Sunda dan Indonesia. Ia juga mendirikan organisasi agama dan
pergerakan nasional Al-Ittihadiyyatul Islamiyyah (1930) yang kemudian berfusi
menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI) serta dipilih sebagai anggota Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945.
Pistol dan
Tasbih
Dalam perjalanan berikutnya, Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942,
lalu Jepang menjalankan kebijakan politik yang berbeda dengan Belanda. Demi
meraih dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang berjanji akan memberi
kemerdekaan. Demi meraih dukungan itu pula, Jepang merekrut banyak orang
Indonesia dan tokoh ummat Islam untuk menjalankan pemerintahan dan menempati
jabatan tinggi. Jepang kekurangan pegawai untuk mengelola birokrasi, karena
kapal mereka yang membawa aparat birokrasi dari negerinya ditenggelamkan
pasukan sekutu dengan senjata torpedo.
KH Hasjim Asj’ari, hadratus syaikh
Nahdlatul Ulama misalnya, diangkat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (Shumubu) yang kegiatan sehari-hari
dilaksanakan putranya KH Wahid Hasjim. Sedangkan KH Ahmad Sanusi diangkat
sebagai wakil residen Bogor (Fuku Shucokan), yang membawahi Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi.
Para tokoh Islam ditunjuk mengikuti pelatihan militer Pembela Tanah Air
(PETA) di Bogor
(sekarang menjadi Pusat Pendidikan Zeni). Di antaranya ialah Soedirman, yang
kelak menjadi Panglima Besar TNI; Kasman Singodimedjo yang kelak menjadi ketua Mahkamah Agung pertama RI;
dan Abdullah bin Nuh, yang ditunjuk sebagai komandan batalyon (Daidanco) untuk
wilayah Bogor,
Sukabumi, dan Cianjur, bermarkas di Ujung Genteng-Jampang Kulon, Sukabumi.
Saat kemerdekaan tiba, Abdullah bin Nuh ditunjuk
sebagai Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR)—cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI)--Sukabumi dan ketua Partai Masyumi se-Keresidenan Bogor. Penampilan Abdullah bin Nuh sebagai komandan dituturkan oleh
rekan seperjuangannya, KH Dadun Abdul Qohhar. “Mama’ Abdullah bin Nuh sering
terlihat naik kuda, dengan pistol di pinggang sambil memegang tasbih di
tangan,” kata KH Dadun Abdul Qohhar. Sungguh sebuah kombinasi menarik: pistol
dan tasbih.
Dari komandan tentara, KH Abdullah bin Nuh diangkat menjadi anggota
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP): lembaga legislatif sebelum ada Dewan
Perwakilan Rakyat. Ketika Jakarta diduduki tentara Sekutu, ia ikut hijrah
bersama pemerintah RI ke Yogyakarta. Di kota gudeg ini, ia ditunjuk sebagai
kepala seksi siaran bahasa Arab di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogya,
sekaligus koresponden Kantor Berita APB (Arabian Press Board). Melalui siaran
berbahasa Arab inilah kemerdekaan Indonesia diketahui dan didukung
bangsa-bangsa Arab. Di Yogya, ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Guru dan Senat
University Islam Indonesia (UII).
Namun Yogyakarta kemudian diduduki Belanda pada Agresi
Militer II, Desember 1948. Bersama
rekan-rekan seperjuangannya, ia menyingkir ke pedalaman dan ikut bergerilya. Di
kala tinggal di Argosari, ia dinikahkan dengan Mursyidah binti H. Abdullah
Sayuti di Kebarongan, Banyumas, pada 5 juni 1949.
Ilmuwan yang
Mumpuni
Usai revolusi, Abdullah bin Nuh tinggal di Jakarta (1950-1970). Dunia
pendidikan kembali memanggilnya. Ia mengajar di perguruan tinggi terkemuka,
Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) pada 1960-1967, tanpa meninggalkan
mengajar di sejumlah pengajian serta majelis taklim. Ia juga menjabat kepala
seksi bahasa Arab RRI Jakarta (1950-1964) dan menjadi pimpinan majalah Syunul
Indonesia edisi bahasa Arab yang diterbitkan Departemen Penerangan. Sebagai
ilmuwan, tak lupa pula ia mendirikan Islamic
Research Institute.
Rekan-rekan dan mantan muridnya di FSUI
mengenangnya sebagai dosen yang kaya ilmu, bertutur lemah-lembut dan mampu
mengajar dengan terang-benderang, sebagaimana ia menulis dan menerjemahkan
berbagai buku. Abdullah bin Nuh menerjemahkan karya Imam Al-Ghazali Pembebas
dari Kesesatan (Al-Munqizu min adh-dhalal) setebal 79 halaman pada
1961, dengan menambahkan keterangan sekitar 200 catatan kaki. Keterangan
tersebut begitu jelas dan rinci sehingga non-muslim pun dapat mengerti isi buku
tersebut. Kendati diterjemahkan lebih dari 50 tahun silam, bahasa yang
digunakannya nyaris tak ketinggalan zaman. Para pembaca di masa kini tetap
dapat menikmati terjemahan itu.
Abdullah bin Nuh memang dikenal sebagai ahli dan mencintai tasawuf Al-Ghazali.
Tak heran bila ia mendirikan majelis taklim di Kota Paris, Bogor, yang dinamai Al-Ghazali pada 1968. Majelis ini kemudian
berkembang menjadi pesantren dan sekolah. Setelah Al-Ghazali berdiri, ia
menetap di Bogor sejak 1971 hingga akhir hayatnya tiba pada 26 Oktober 1987.
Namun pemerintah Orde Baru merintangi kegiatan dan pengembangan
Pesantren Al-Ghazali karena KH Abdullah
bin Nuh tidak mendukung Golkar dalam seluruh Pemilihan Umum. Bahkan pada Pemilu
1982, ia sempat ditahan pemerintah sekitar dua pekan lamanya. “Saya yang
menjemputnya pulang dari Korem di Bogor,” kata H. Ujang Damanhuri, pengurus Partai Persatuan Pembangunan Leuwiliang, Bogor.
Di Kota Hujan itu, bersama rekan-rekan
seperjuangannya sejak zaman revolusi, yakni,
KH Sholeh Iskandar, KH Noer Alie, KH Choer Affandi, KH Abdullah Syafi’i, dkk., ia mendirikan
organisasi Badan Kerja Sama Pondok Pesantren (BKSPP) Jawa Barat pada 1972; lalu
mendirikan majelis taklim Al-Ihya di Pasir Jaya, Bogor.
Sepanjang hayatnya, KH Abdullah bin Nuh menulis 28 buku dan
menerjemahkan 8 buku, yang meliputi bidang bahasa (kamus), sastra, sejarah,
tasawuf, dan fikih. Salah satu syairnya, “Persaudaraan Islam”, yang ditulisnya ketika mengajar di Hadramaut School
tahun 1925, begitu terkenal hingga “diabadikan” para penggemarnya di dunia maya
dan dapat ditemui dengan mudah melalui mesin pencari kata Google. Puisi ini
dilukis di salah satu ruangan di Istana Raja Yordania.
Belasan tahun setelah kepergiannya, Pemerintah Kabupaten Cianjur
mengusulkan KH Abdullah bin Nuh sebagai pahlawan nasional pada 2010.
***
Sumber:
1. Abdullah bin Nuh & Oemar Bakry, Kamus
Indonesia-Arab-Inggeris (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1991).
2. A. Dwi Pamudji (et.al), 60 Tahun
Universitas Islam Indonesia Berkiprah dalam Pendidikan Nasional (Jakarta:
Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 2004)
3. Ika Nurmaya, K.H.R. Abdullah bin Nuh,
Riwayat Hidup dan Beberapa Pemikirannya (Skripsi Jurusan Asia Barat,
Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1992.
4. Wawancara dengan K.H. Dadun Abdul Qohhar di Bogor, Maret 2004
5. Wawancara dengan Prof. Machasin, Oktober 2008
di Jakarta.
6. Wawancara dengan H. Ujang Damanhuri, di
Warung Saptu, Cibungbulang, Bogor,17 Februari 2015
Sunday, July 5, 2015
JJ Rizal tentang Bogor Masa Revolusi
Jj Rizal menambahkan 3 foto baru.
Buku baru @komunitasbambu Bogor Masa Revolusi 1945-1950: Sholeh
Iskandar dan Batalyon O Siliwangi karya senior saya, Edi Sudarjat. Ia dulu
seperti saya adalah mahasiswa sejarah di FSUI (kini FIB UI) dan terutama
cemerlang dalam sejarah pergerakan nasional sampai revolusi Indonesia. Ia
senior dari kelompok Islam yang kalau menulis mengingatkan saya pada alamarhum
pak Deliar Noer. Sangat berwibawa karena kekuatan analisis dan datanya, tetapi
menarik juga karena kang Edi, begitu saya memanggilnya, memiliki gaya narasi sastera. Sebagai
mahasiswa ia termasuk yang banyak mendapat ruang menulis di Koran Republika
pada masa-masa emasnya tahun 1990an yang melahirkan serta memanggungkan banyak
intelektual Islam Indonesia.
Tahun lalu saya diundang dia untuk mengikuti presentasi risetnya
tentang revolusi di Bogor yang di dalamnya memainkan peran penting intelektual
tentara religius, Sholeh Iskandar. Seperti biasa selalu senang mendegarnya
karena bukan saja berkisah, tetapi juga menunjukkan ekspresi total untuk
memasuki dan memahami alam pikiran zaman bersiap serta perasaan tokoh-tokohnya
bukan saja yang elit tetapi juga yang alit, sebut saja kisah laskar rakyat.
Seperti biasa kekuatannya dalam data pustaka dan arsip diperkaya oleh wawancara
yang luas yang menjadi basis sebuah sejarah lisan sebagai sumber yang
memungkinkan suara dan kisah yang tidak tercatat bahkan dihapuskan tampil.
Alhasil buku bukan saja sapuan-sapuan besar tetapi juga petit
histoire atau sejarah kecil berkelindan bersuara, bercerita sejarah. Apalagi
dilengkapinya pula dengan sejumlah foto-foto dari arsip koran, majalah sezaman
dan teristimewa foto koleksi pribadi orang-orang yang terlibat revolusi di
Bogor itu. Sungguh buku kecil yang menggugah itu menggembirakan sekali bisa
saya bantu penerbitannya, buku sejarah yang membacanya berasa mendapat pahala,
kalo ga percaya silakan pesan ke pemasaran@komunitasbambu.com
Wednesday, June 24, 2015
"Hanura: Bakal Besar atau Gurem?" Koran Tempo, 22 Agustus 2008
Hanura: Bakal Besar atau Gurem?
Koran Tempo, 22 Agustus 2008
Edi Sudarjat, peneliti di Indonesian Research and Development Institute
Belakangan ini sering kita dengar
pertanyaan berapa suara yang akan diraih Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)?
Apakah Hanura akan menjadi partai besar yang mampu menerobos ke jajaran tujuh
partai besar yang menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat?
Pertanyaan di atas, berikut perhitungan
orang bahwa Hanura akan menjadi partai besar, merupakan hal yang wajar.
Pertimbangan orang adalah, pertama, Hanura dipimpin tokoh ternama, Wiranto,
mantan Panglima TNI serta Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan. Dalam
jagat politik di Indonesia
Kedua, ketika Wiranto maju menjadi calon
presiden resmi dari Partai Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid pada
pemilihan presiden 2004, Wiranto sukses mendulang 22,15 persen suara. Cukup
banyak orang yang berpikir, perolehan suara tersebut merupakan modal penting
untuk bertarung dalam Pemilu 2009. Kemudian orang menggunakan matematika
sederhana (yang sebenarnya menyesatkan) sebagai berikut: jika Wiranto berhasil
mengumpulkan suara setengah dari suaranya di waktu pemilihan presiden dulu,
Hanura bakal meraih 11 persen suara. Artinya, Hanura akan bertengger di posisi
ketiga, setelah Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang
pada Pemilu 2004 meraih 21,6 persen dan 18 persen suara.
Ketiga, Hanura berhasil menarik sejumlah
tokoh masyarakat dan pengurus dari partai politik lainnya ke dalam jajaran
pengurusnya. Keempat, para pengurus Hanura tampaknya memiliki dompet cukup
tebal. Hal ini terlihat dari kantor-kantor Hanura di kota-kota besar di Indonesia
*
Berbeda dengan pertimbangan kebanyakan
orang seperti di atas, kita akan menganalisis seberapa besar kemungkinan
perolehan suara Hanura berdasarkan dua kali survei nasional Indonesian Research
and Development Institute (IRDI), yang dilakukan pada Maret 2008 dan Juli 2008.
Responden survei ini berjumlah 2.600 orang--jumlah responden terbesar dalam
survei politik di Indonesia Indonesia
Dari survei nasional IRDI pada Juli 2008,
diketahui bahwa mayoritas responden (84,8 persen) tidak mengenal partai baru;
yang mengenal hanya 15,2 persen. Yang menarik, partai baru yang paling mereka
kenal adalah Hanura: 11,4 persen. Angka pengenalan ini meningkat dibanding
survei IRDI pada Maret 2008. Saat itu Hanura dikenal 7 persen responden. Dengan
demikian, kerja keras Hanura memperkenalkan dan mempopulerkan dirinya tergolong
baik.
Dibanding lusinan partai baru lainnya,
tingkat pengenalan orang atas Hanura sangat tinggi. Partai baru lainnya cuma
dikenal segelintir responden, dengan perincian sebagai berikut: Gerindra
dikenal 1,14 persen responden; Partai Kebangkitan Nasional Ulama dikenal 0,71
persen responden; Partai Demokrasi Pembaruan 0,51 persen; Partai Peduli Rakyat
Nasional 0,39 persen; Partai Matahari Bangsa 0,24 persen; Partai Karya
Perjuangan 0,08 persen; Partai Patriot 0,08 persen; Partai Republikan 0,08
persen; Partai Buruh 0,08 persen; dan Partai Demokrat Sejahtera 0,08 persen.
Berbeda dengan popularitasnya yang tinggi,
tingkat kedekatan responden dengan Hanura sangat rendah, hanya 1,74 persen.
Apalagi tingkat keterpilihan (elektabilitas) Hanura, benar-benar sangat rendah:
0,36 persen. Elektabilitas ini diukur dengan pertanyaan, "Jika pemilihan
umum dilakukan hari ini, partai manakah yang akan Anda pilih?" Pada survei
IRDI Juli 2008, responden yang memilih PDIP 26,3 persen; yang memilih Golkar
24,6 persen; Partai Demokrat (PD) 11,2 persen; Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9,12; dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 persen. Posisi berikutnya ditempati
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 persen; Partai Amanat Nasional (PAN) 3,27
persen; Partai Bulan Bintang 0,5 persen; Partai Bintang Reformasi 0,38 persen;
dan Hanura 0,36 persen.
Dengan demikian, jika pemilu dilakukan
pada Juli 2008, Hanura akan memperoleh suara sekitar 0,36 persen. Untuk
menyamai PAN, yang menempati urutan ketujuh pada Pemilu 2004 dan urutan ketujuh
pada survei nasional IRDI Juli 2008 dengan elektabilitas 3,27 persen, Hanura
mesti menggenjot elektabilitasnya dari 0,36 persen mencapai 3,27 persen.
Artinya, Hanura harus meningkatkan elektabilitasnya sembilan kali lipat lebih
atau 908 persen!
Mengingat Pemilu 2009 akan dilaksanakan
sembilan bulan lagi, mampukah Hanura mendongkrak elektabilitas
sekurang-kurangnya 908 persen dalam waktu sembilan bulan? Rasanya benar-benar
sulit. Peningkatan elektabilitas ini, selain melalui kampanye, bisa dengan
menyedot suara partai lain. Misalnya Hanura menyedot suara dari pemilih Golkar,
mengingat Wiranto dulu kandidat presiden dari Golkar. Harapan lainnya adalah
Hanura menampung suara yang lari dari PD. Sebagai partai baru, PD belum
memiliki basis massa
Namun, menyedot suara yang lari dari
Golkar tidak mudah dilakukan. Soalnya, pemilih Golkar loyalitasnya sangat
tinggi, 79,25 persen. Artinya, responden yang memilih Golkar pada Pemilu 2004
dan pada Juli 2008 telah memutuskan akan memilih Golkar lagi pada 2009
berjumlah 79,25 persen. Menyedot suara dari PD lebih mudah dilakukan lantaran
loyalitas pemilih PD tidak begitu tinggi, yakni 44,3 persen.
Masalahnya, Hanura mesti berebut dengan
partai-partai lain untuk memikat pemilih PD. Bersamaan dengan itu, mesti
diasumsikan bahwa sampai Pemilu 2009 pengurus PD tidak banyak berbuat untuk
menarik kembali pemilihnya. Rasanya asumsi ini juga sulit berlaku, mengingat
menjelang pemilu seluruh partai pasti bergerak lebih cepat dan lebih lincah.
Alhasil, jika tidak ada momentum politik yang menguntungkan Hanura
dalam sembilan bulan ke depan dan kondisi tetap stabil seperti sekarang, dapat
diduga Hanura tidak akan mampu menerobos ke posisi tujuh partai besar.***
Resensi: Biografi Tokoh NU: Permata yang Belum Dipoles
UMMAT, 21 Desember 1998
Biografi Tokoh NU: Permata
yang Belum Dipoles
Buku ini berhasil melukiskan aneka ragam sosok kiai NU. Toh, beberapa
faktanya mesti dikoreksi
Saifullah Ma’shum, (ed.), Karisma Ulama:
Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU (Mizan dan Yayasan Saifuddin Zuhri, Bandung:
1998); 395 hlm.
|
K
|
iranya tak melesetlah apa yang dikatakan KH A.
Mustofa Bisri dalam kata pengantarnya bahwa buku ini sudah lama dinanti dan
sering diusulkan oleh banyak warga Nahdlatul Ulama (NU) di berbagai kesempatan. Soalnya, sambung Kiai
Mustofa Bisri, tradisi menulis sejarah kehidupan para tokohnya tak berkembang
di kalangan pesantren NU.
Walhasi, kondisi ini boleh dibilang
memprihatinkan, mengingat NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia—dengan
30 juta anggota—dan telah berusia 72 tahun.
Mengapa
hanya 26 tokoh? Bukankan NU memiliki ratusan tokoh lagi yang pantas dikenang
riwayat hidupnya?
Pihak
Yayasan Saifuddin Zuhri menjelaskan, jumlah 26 tokoh ini tak lain merupakan
hasil kompromi tiga hal: (1) sejauhmana keberhasilan menghimpun informasi; (2)
adanya keterbatasan waktu penelitian; (3) keterbatasan daya dukung lain yang
diperlukan untuk penulisan.
Lalu,
dirumuskan bahwa mereka yang memenuhi kriteria tokoh ialah para kiai yang
pernah menjadi pengurus syuriah, mutasyar atau jabatan struktural lain dalam NU
pada tingkat nasional atau lokal. Juga mereka yang memimpin pesatren dan kini
sudah wafat.
Boleh
dibiliang buku ini relatif berhasil melukiskan aneka ragam sosok kiai NU, yang
dengan caranya sendiri-sendiri telah meninggalkan jejak penting dalam dakwah
dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hampir seluruh tokoh kiai dalam buku ini
giat menenang penjajahan Belanda, sekaligus aktif dalam revolusi fisik.
Keberhasilan
itu rupanya karena tim penulisnya mampu memaparkan riwayat sejumlah kiai yang
kurang begitu terdengar namanya di luar tubuh NU, semisal Hasan Gipo, KH Abas,
KH Thohr Bakri, dan KH Abdullah Ubaid. Jadi, bukan cuma memuat deretan nama
kondang, seperti Kiai Cholil, KH R. Asnawi, KH Mas’shum, H Hasyim Asy’ari, KH
Bisri Syansuri, KH Wahab Chasbullah, dan KH Wahid Hasyim.
Lewat
riwayat ringkas mereka, terlihat pula dinamika internal NU dalam menghadapi
perubahan zaman, suatu hal yang jarang ditelaah dalam buku lain tentang NU yang
kebanyakan menyorot sisi politiknya. Simaklah riwayat KH Thohir Bakri. Pada dasawarsa
1930-an, ia adalah aktivis muda yang giat memikirkan pembentukan organisasi
pemuda NU. Berkat ketekunannyalah NU kemudian memiliki barisan pemuda yang
cukup dikenal: Ansoru Nahdlatoel Olema (ANO)—kini GP Ansor.
Toh,
dalam perjalanan pembentukan ANO, Thohir sempat “bertabrakan” dengan para ulama
sepuh yang mengharamkan drumband dan
dasi yang justru merupakan atribut kebanggaan para pemuda. Alsannya, dasi
menyerupai (tasyabbuh) orang kafir
(Belanda). Akibatnya, persoalan ini menjadi sumber ketegangan empat kali
muktamar NU, dari muktamar ke-12 (1937) sampai ke-15 (1940). Barulah pada
muktamar ke-15, drumband dan dasi
diperbolehkan. Ini pun melalui sidang yang alot dan melakukan voting (hlm. 252). Tentu perdebatan
keras ini hanya pencerminan dinamika NU dalam menghadapi perubahan da bidang
lain yang tak kalah pentingnya.
Ditinjau
dari metodologi sejarah, buku ini termasuk kategori biografi sumber, yaitu
biografi pertama yang ditulis mengenai seorang tokoh. Dengan demikian,
penulisnya tidak wajib membuat perbandingan dengan biografi lain dan tidak
perlu membuat analisis atau deskripsi interpretatif. Yang penting adalah
mengemukakan sebanyak mungkin fakta mengenai keidupan tokohnya yang disajikan
dengan menarik.
Tentu
dalam mengemukakan fakta tersebut, akurasi dan kelengkapan data dasar merupakan
syarat yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Nah, dua hal inilah titik lemah
buku Karisma Ulama. Sejumlah fakta
dasar buku ini kurang lengkap dan tanpa standarisasi, malah ada yang keliru
agak fatal. Misalnya, sejumlah kiai disebutkan nama istri dan anaknya, tapi ada
pula yang “terlupakan”. Berikutnya dalam
riwayat KH Bisri Mustofa—ayahanda KH Mustofa Bisri—dituliskan ia sakit mata dan
memerlukan kornea untuk pengobatan (hlm. 325). Kenyataannya yang sakit bukan KH
Bisri, melainkan istrinya, Ny. Ma’rufah binti Cholil.
Mengingat
langkanya biografi tokoh NU, sebenarnya kehadiran buku ini bak permata
pengetahuan mengenai sejarah organisasi Islam terbesar di Nusantara itu. Sayang
permata ini mesti dipoles lagi agar berkilau.*** (Edi Sudarjat)
Tuesday, June 23, 2015
Resensi: Asal-usul Konflik Etnis Madura-Dayak
REPUBLIKA - Minggu, 30 Desember
2001
Asal-usul
Konflik Etnis Madura-Dayak
Inilah disertasi yang paling sering disebut orang ketika membicarakan konflik etnis Madura dan Dayak di Kalimantan Barat (Kalbar). Sejatinya, penelitian almarhum Hendro bukan membahas konflik etnis, melainkan migrasi swakarsa orang Madura ke Kalbar. Namun selain memaparkan latar belakang, faktor-faktor pendorong dan penarik migrasi, ia juga meneliti hubungan dan pandangan orang Madura terhadap suku lainnya di Kalbar.
Buku yang diterbitkan oleh ISAI (Isntitut Studi Arus Informasi) ini menjelaskan hubungan dan pandangan orang Madura terhadap orang Bugis, Melayu, Cina, dan Dayak. Tak alpa pula ia menelaah penyebab konflik antara etnis Madura dan Dayak yang berlangsung sebelum tahun 1984 --saat disertasi ini ditulis. Pada bagian inilah ia menyumbangkan pengetahuan yang sangat berharga.
Hendro menjaring informasi lewat pengumpulan sumber primer dan sekunder, serta menyebar 400 kuesioner tipe pilihan kepada para migran asal Madura, ditambah wawancara terhadap puluhan informan kunci. Ia menggunakan konsep yang kini marak dibicarakan orang, yakni prasangka, stereotipe, etnosentrisme, konflik, konsiliasi, asimilasi dan permusuhan terbuka. Kalaupun ada kelemahan dalam disertasi ini adalah: ia tidak menggunakan sumber informasi sezaman pada periode yang ia teliti, semisal arsip, koran, dan majalah.
Berdasarkan data dan pengamatan Hendro, migrasi swakarsa orang Madura ke Kalbar telah berlangsung lama, tepatnya sejak 1902. Kebanyakan mereka berasal dari dua kabupaten di bagian barat pulau garam itu, yakni Bangkalan dan Sampang. Mengapa? Pada dua kabupaten inilah penduduknya paling banyak (hlm. 50).
Penduduk Madura memang padat. Seperti diurai dalam disertasi Huub de Jonge (1989: 21), sejak 1815 sampai 1940 penduduk Madura malah lebih padat dari pulau Jawa. Artinya sampai 1940 Madura adalah pulau terpadat penduduknya di Indonesia. Kepadatan penduduk yang tinggi ini berakibat pada sempitnya pemilikan tanah: rata-rata 0,3 ha per orang (hlm. 57). Faktor pendorong migrasi lainnya adalah tanah di Madura tergolong gersang.
Kepadatan penduduk, tanah gersang, keberanian dan kebiasaan bermigrasi, ditambah satu pendukung berlangsungnya migrasi yang juga penting, yakni tersedianya armada kapal layar Madura yang mampu menjangkau wilayah jauh, sampai ke Semenanjung Malaya.
Adapun Kalbar menjadi daerah tujuan migrasi lantaran kepadatan penduduknya rendah. Pada 1980 hanya 17 jiwa per km persegi. Kalbar jelas membutuhkan pekerja untuk mengolah kekayaan alam dan membangun infra struktur perekonomiannya. Dan kebutuhan ini, terutama pekerja kasar, diisi orang Madura.
Para juragan kapal yang sering bolak-balik ke Kalbarlah yang mula-mula membawa mereka ke sana. Bila calon migran tidak punya ongkos, juragan kapal bersedia menanggungnya lebih dahulu, dengan perjanjian akan dilunasi setelah mereka bekerja di Kalbar. Para migran ini dipikat lewat "janji surga" betapa gampangnya mencari kekayaan di tanah seberang. Pemeo yang kondang saat itu ialah, "Sejengkal memotong akar pinang, mendapat uang 50 ketip."
Ternyata mulut manis juragan kapal itu 'berbisa.' Sesampainya di Kalbar para migran tersebut 'dijual' layaknya perbudakan terselubung! Zaman penuh kepedihan dan penderitaan ini -- yang sangat jarang diceritakan kepada anak cucunya -- disebut 'Periode Perintisan' (1902-1942). Setelah itu disambung "Periode Surut" (1942-1950) lantaran masuknya Jepang dan meletusnya revolusi kemerdekaan.
Setelah bertahun-tahun membanting tulang akhirnya para migran itu tiba pada 'Periode Keberhasilan' (1950-1980). Pada masa ini mereka hidup layak. Mereka memiliki rumah dan kebun, bahkan menguasai sektor-sektor ekonomi informal tertentu, semisal penarik becak, penambang sampan, dan pekerja jalan darat (hlm. 84).
Apa yang membuat mereka berhasil? Hendro melihat sejumlah faktor, antara lain, pertama, mereka memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang kuat sehingga sanggup bekerja keras, menderita, dan hidup hemat. Etos kerja ini didorong rasa malu (todus) yang tercermin dalam pepatah Ango'an potea tolang, e tebang pote mata (lebih baik putih tulang, daripada putih mata). Maknanya adalah lebih baik mati daripada gagal dalam kehidupan di rantau (hlm. 81).
Kedua, solidaritas sosial mereka sangat tinggi. Banyak migran Madura ke Kalbar tanpa membawa modal usaha sepeser pun. Mereka yakin, keluarga atau teman-temannya di rantau akan membantu. Kombinasi solidaritas dan kerja keras itu membuat mereka menguasai sektor-sektor perdagangan tertentu, sehingga orang-orang non Madura yang lebih dulu bergerak di bidang itu terdesak, bahkan terlempar keluar.
Belakangan, soal ini menjadi salah satu faktor penyebab meletusnya konflik etnis Madura melawan Melayu di Sambas, Kalbar. Pasalnya, migran Madura acap merebut kesempatan kerja dan pemilikan barang melalui kekerasan atau intimidasi --tidak lagi melalui jalan yang sah. (Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie, "Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis", Antropologi Indonesia, Th XXIII, No. 58, 1999, hlm.41)
Lantas, faktor apa saja yang menimbulkan konflik? Hendro mencatat, pertama, sifat dan kelakuan dari 'tanah air' (rasa kesukuan atau ethnic urbanism) di Madura dibawa serta bermigrasi. Adat carok dan solidaritas kuat -meski acap membabi buta-- mereka bawa ke Kalbar. Akibatnya pertengkaran antar individu segera menjelma menjadi pertengkaran antar kelompok. Perkelahian antar kelompok kontan berkobar menjadi perang suku.
Kedua, pola pemukiman reng Madure kebanyakan pola kelompok, bukan pola sisipan. Ini membuat proses asimilasi dengan warga setempat terhalang.
Ketiga, tingkat pendidikan para migran sangat rendah. Otomatis mereka sulit mengunyah-nguyah informasi, beradaptasi, dan hanya mampu menguasai sektor formal. Dari 400 responden penelitian Hendro, 79 persen di antaranya tidak sekolah/buta huruf dan 10 persen lagi tidak tamat SD.
Hubungan etnis Madura-Dayak kurang harmonis antara lain karena faktor-faktor tersebut di atas. Sifat keras orang Madura, juga terdapat pada orang Dayak. Tingkat pendidikan dan posisi ekonomi kedua suku ini hampir sejajar: sama-sama rendah dan mengisi sektor informal. Sementara agama dan adat mereka berbeda. Di sisi lain hubungan etnis Madura-Bugis di Kalbar rukun lantaran faktor kesamaan agama.
Rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia pada kedua suku itu menambah kekurangharmonisan. Orang Madura menggunakan bahasa Indonesia dialek Madura yang kurang sempurna. Sedangkan orang Dayak berbahasa Indonesia aksen Dayak yang juga kurang sempurna. Intonasi meledak-ledak sebagai pencerminan dari sifat etnis Madura yang keras, mudah menimbulkan salah paham.
Toh, kekurangharmonisan ini tidak berarti kedua suku itu tidak melakukan kontak sosial. Hubungan sosial mereka diwarnai sikap prasangka dan menjaga jarak. Yang menggembirakan bahwa di beberapa kampung, seperti di Sungai Ambawang dan Marga Mulia, terjadi perkawinan antara orang Madura dan Dayak. Hendro berharap, seandainya perkawinan macam ini makin banyak, lambat laun kekurangharmonisan dalam pergaulan sosial mereka akan berkurang (hlm. 140).
Ternyata harapan mulia penulis buku ini sekarang tinggal kenangan belaka. Setelah disertasi ini ditulis, konflik Madura-Dayak malah memuncak dan berlarut-larut hingga kini. Betapapun demikian, buku ini menjadi penting lantaran mampu menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dan membuka jalan untuk rekonsiliasi.
Edi Sudarjat, Peneliti pada Centre for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) Jakarta
Subscribe to:
Posts (Atom)